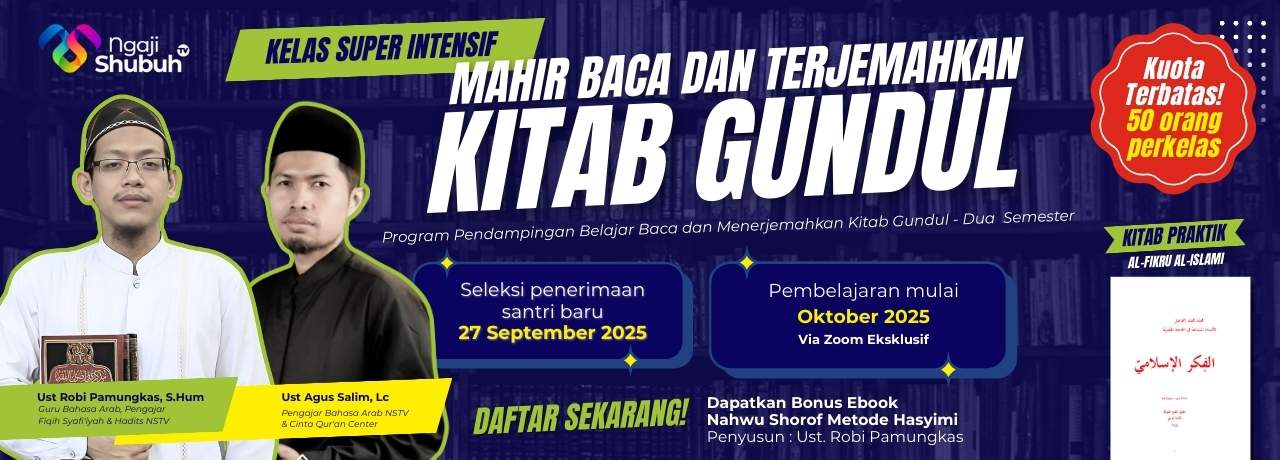Memahami Pajak dalam Islam: Studi Persamaan dan Perbedaan dengan Kapitalisme
Akhir-akhir ini, isu pajak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai protes muncul terkait kenaikan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan di Pati Jawa Tengah dan Bone Sulawesi Selatan. Isu ini semakin relevan setelah adanya pernyataan dari Menteri Keuangan yang menyamakan pajak dengan wakaf atau zakat, yang kemudian menimbulkan pro dan kontra.
Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam mengenai pajak? Apakah pajak diharamkan secara mutlak dalam syariat Islam, atau justru ada ruang bagi pungutan ini?
Definisi Pajak: Antara Hukum Nasional dan Syariat Islam
Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Poin intinya adalah negara memungut dari rakyat untuk keperluan negara, yang pada akhirnya dikembalikan untuk manfaat rakyat.
Dalam Islam, sebenarnya juga ada konsep pungutan serupa. Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizhamul Islam halaman 86 menyebutkan istilah “dharibah” (pajak), yang diartikan sebagai “harta yang diambil dari warga negara untuk pengelolaan berbagai urusan negara“. Definisi ini memiliki tiga unsur kesamaan dengan definisi pajak di Indonesia: yang memungut adalah negara, yang dipungut adalah warga negara, dan tujuannya untuk keperluan negara.
Para ulama dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali) juga memiliki istilah-istilah tersendiri yang maknanya merujuk pada pajak:
- Mazhab Hanafi: Menggunakan istilah an-Nawaib (disebut dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin).
- Mazhab Maliki: Menggunakan istilah al-Wadif (disebut dalam kitab Al-Bahjah karya Imam at-Tasuli).
- Mazhab Syafi’i: Menggunakan istilah at-Taudzif.
- Mazhab Hambali: Menggunakan istilah al-Kulfus Sulthaniyah (beban pungutan dari negara).
Istilah-istilah ini berbeda, namun intinya sama, yaitu pungutan dari negara kepada rakyat di luar zakat, yang diperlukan saat Baitul Mal (kas negara) kosong.
Bolehkah Pajak dalam Syariah Islam?
Dari segi istilah, penggunaan kata “pajak” (atau dharibah dalam bahasa Arab modern) dalam ekonomi Barat atau kapitalisme boleh dipakai umat Islam. Ini karena faktanya Islam juga membolehkan negara untuk mengambil harta dari warga negara guna memenuhi keperluan negara.
Namun, dari segi hukum terdapat perbedaan mendasar:
- Pajak dalam kapitalisme diatur oleh hukum sekuler yang tidak bersumber dari Al-Qur’an atau hadits.
- Pajak dalam Islam harus diatur berdasarkan syariah, di mana setiap pasal atau aturan harus memiliki dalil dari Al-Qur’an atau hadits.
Legitimasi pajak dalam Islam terletak pada adanya kewajiban bersama yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada dua pihak secara simultan: kepada khalifah atau negara, dan pada saat yang sama, kepada umat Islam. Untuk menjalankan kewajiban ini, jika dana dari Baitul Mal tidak mencukupi, barulah pajak boleh dipungut.
Contoh kewajiban bersama yang dimaksud adalah menyantuni fakir dan miskin. Ini adalah kewajiban negara (melalui khalifah) berdasarkan firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103: “Ambillah olehmu dari harta-harta mereka sedekah (zakat)…” Zakat disalurkan kepada delapan golongan, termasuk fakir dan miskin, seperti yang termaktub dalam Surah At-Taubah ayat 60.
Pada saat yang sama, membantu fakir dan miskin juga merupakan kewajiban individu umat Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidak sempurna iman seseorang kepadaku, barangsiapa yang tertidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangga di sebelah rumahnya kelaparan dan dia mengetahuinya.”
Jika untuk memenuhi kewajiban bersama ini dana di Baitul Mal tidak ada atau kurang, maka khalifah boleh mewajibkan pajak atas kaum Muslim sesuai ketentuan syariah. Jika kondisinya sangat mendesak (misalnya ancaman kelaparan), negara dapat meminjam dana (akad qardh) dari rakyat yang kaya terlebih dahulu, kemudian mengembalikan pinjaman tersebut dari hasil pungutan pajak yang dilakukan setelah kondisi mendesak teratasi. Jika tidak mendesak, negara dapat langsung memungut pajak.
Pajak yang Tidak Syar’i (Tidak Sesuai Syariat)
Jika penguasa memungut pajak untuk sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, bahkan tidak ada dalilnya dari Al-Qur’an atau hadits, maka pungutan tersebut tidak sah secara syariah. Contohnya:
- Pajak untuk keperluan yang hukumnya tidak wajib, seperti pindah ibu kota padahal ibu kota lama masih layak.
- Pajak untuk membayar riba (bunga utang), seperti bunga utang luar negeri. Riba jelas diharamkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang menyatakan dosa 1 dirham riba lebih besar daripada 36 kali berzina. Di Indonesia, pada tahun 2025, bunga utang yang harus dibayar pemerintah mencapai Rp552,1 triliun, yang dibayar dari uang pajak rakyat.
Pungutan pajak yang tidak syar’i seperti ini diancam oleh Allah, dan pelakunya tidak akan masuk surga. Inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW: “La yadkhulul jannata shahibu maksin (Tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai atau pajak yang tidak syar’i).” Makna al-maks dalam hadits ini adalah pungutan yang melanggar syariat, bukan berarti semua jenis pajak secara mutlak diharamkan.
Pinjaman Luar Negeri dalam Islam
Negara Khilafah boleh meminjam dari luar negeri dengan dua syarat penting; (1) Tidak mengandung riba (bunga), dan (2) Tidak mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negara.
Pinjaman tidak boleh menjadi instrumen dominasi oleh negara atau lembaga keuangan asing, yang bisa menyetir kebijakan politik dan ekonomi negara peminjam.
Persamaan dan Perbedaan Pajak dalam Kapitalisme dan Islam
Persamaan:
- Bersifat memaksa: Baik dalam kapitalisme maupun Islam, pajak bersifat wajib dan memaksa.
- Bentuk pembayaran: Dibayar dalam bentuk uang.
- Imbalan langsung: Tidak ada imbalan langsung yang diterima pembayar pajak.
- Tujuan: Untuk memenuhi keperluan negara (meskipun dengan perbedaan dalam peruntukan, terutama terkait utang).
Perbedaan:
- Dasar Kewajiban:
Kapitalisme: Berdasarkan teori-teori ekonomi (misalnya teori asuransi, teori bakti, teori daya pikul).
Islam: Berdasarkan wahyu dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, yaitu untuk menjalankan kewajiban bersama antara negara dan rakyat.
- Sumber Pendapatan Negara:
Kapitalisme: Pajak adalah sumber pendapatan negara yang tetap.
Islam: Pajak (dharibah) adalah sumber pendapatan negara yang tidak tetap (hanya dipungut jika diperlukan), sedangkan zakat, jizyah, fai, dan ghanimah adalah pendapatan tetap.
- Kontinuitas:
Kapitalisme: Pajak bersifat kontinyu (terus-menerus).
Islam: Pajak bersifat temporal atau tidak kontinyu, yaitu hanya saat kas negara kosong atau tidak mencukupi kebutuhan.
- Metode Mewajibkan:
Kapitalisme: Kewajiban pajak ditetapkan dengan undang-undang yang memerlukan persetujuan legislatif (misalnya DPR).
Islam: Kewajiban pajak ditetapkan oleh khalifah, yang memiliki hak legislasi undang-undang tanpa perlu persetujuan majelis umat.
Kriteria Pajak yang Dibolehkan Syariah
Terdapat empat kriteria utama agar pajak dibolehkan dalam syariat Islam, antara lain:
- Dipungut untuk melaksanakan kewajiban syar’i yang menjadi kewajiban bersama antara negara (Baitul Mal) dan kaum Muslim secara umum. Contohnya, menyantuni fakir dan miskin.
- Bersifat temporal (tidak permanen), yaitu hanya ketika harta di kas negara kosong atau tidak mencukupi kebutuhan.
- Hanya dipungut dari kaum Muslim, tidak boleh dari warga non-Muslim. Untuk warga non-Muslim, ada pungutan tersendiri yang disebut jizyah.
- Hanya dipungut dari warga negara yang mampu, tidak boleh dari orang miskin atau fakir. Kriteria “mampu” merujuk pada mereka yang tidak termasuk delapan asnaf penerima zakat.
Tantangan Penerapan Sistem Pajak Syariah
Penerapan kriteria pajak syariah ini nampaknya mustahil atau tidak mungkin dalam sistem kapitalisme atau sekuler saat ini. Sistem yang ada tidak memperhitungkan Islam sebagai aturan kehidupan. Misalnya, pajak bumi dan bangunan, yang merupakan milik rakyat sendiri, tidak memiliki dasar syariat untuk dipungut. Perubahan menyeluruh pada sistem negara menjadi sistem Islam diperlukan untuk dapat memenuhi keempat syarat tersebut.
Pajak dalam Islam pada dasarnya ada dan dibolehkan, asalkan memenuhi persyaratan menurut syariat Islam itu sendiri. Hal ini menekankan pentingnya pemerintahan yang tunduk pada aturan Allah dan Rasul-Nya demi kemaslahatan rakyat secara menyeluruh.[]