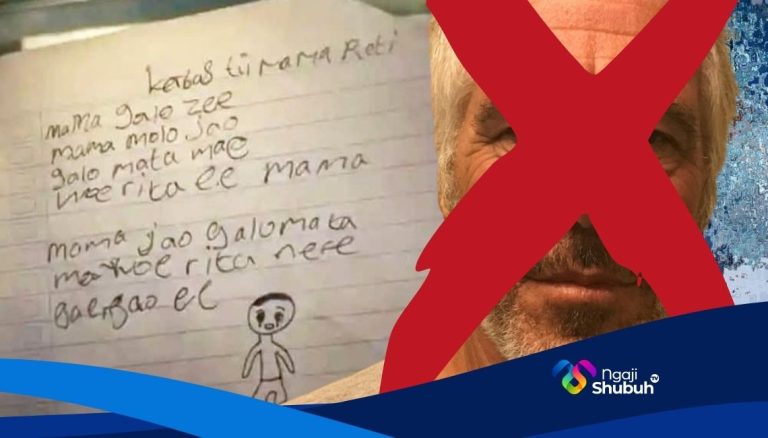Kekuatan di Balik Tinta
Dalam diskursus politik modern, diplomasi sering kali terjebak dalam birokrasi yang gemuk, dokumen ribuan halaman, dan retorika yang sengaja dibuat ambigu. Akan terlihat kontras yang tajam ketika menelaah korespondensi kenegaraan Rasulullah ﷺ. Melalui dokumen sejarah yang dihimpun secara apik oleh Muhammad Hamidullah dalam kitab Majmu’atul Wataq wa al-Rasail, kita menemukan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak terletak pada tumpukan kertas, melainkan pada kejelasan prinsip dan wibawa pemimpinnya. Surat singkat yang dikirimkan kepada Kaisar Heraklius dari Romawi Timur bukan sekadar pesan, melainkan instrumen politik yang mampu membuat penguasa imperium adidaya tersebut bergetar. Inilah diplomasi yang tidak mengemis, melainkan diplomasi yang membebaskan.
Strategi Al-Ijaz bil-Qasri: Keindahan dalam Keringkasan
Dalam ilmu balaghah (retorika Arab), surat-surat Nabi ﷺ merupakan manifestasi puncak dari konsep Al-Ijaz bil-Qasri—meringkas kalimat namun memadatkannya dengan makna yang meluas. Secara politis, gaya komunikasi ini mengirimkan pesan otoritas yang sangat kuat. Seorang pemimpin yang berbicara terlalu banyak sering kali kehilangan wibawanya, namun Nabi ﷺ menunjukkan bahwa keringkasan adalah cerminan kekuatan.
Surat tersebut tidak memerlukan kata pengantar yang berbasa-basi atau pemanis retoris yang kosong. Efisiensi kata ini menunjukkan bahwa negara Islam saat itu memiliki posisi tawar yang tinggi dan tidak sedang mencari pengakuan lewat sanjungan.
“Surat kenegaraan di masa nubuwah adalah puncak retorika politik; ia ditulis dalam bentuk yang ringkas dan padat karena otoritas sejati tidak membutuhkan banyak kata untuk menunjukkan kedaulatannya. Inilah pesan yang membawa bobot dakwah sekaligus peringatan bagi stabilitas imperium dunia.”
Diksi Strategis: Mengapa “Shahibir Rum” Bukan “Maliki Rum”?
Ketelitian Nabi ﷺ dalam pemilihan diksi menunjukkan kecerdasan sosiopolitik yang luar biasa. Beliau menyapa Heraklius dengan kalimat sebutan “Ila Shahibir Rum (kepada Penguasa Romawi)”, secara sadar menghindari istilah Maliki Rum (Raja Romawi).
Analisis ini memberikan dua pemahaman berikut:
- Penghormatan Protokoler: Penggunaan “Shahib” (pemilik/pemimpin) adalah bentuk penghormatan yang tepat sesuai kedudukan objek bicara (Likulli maqamin maqalun), mengakui Heraklius sebagai pemegang otoritas de facto.
- Legitimasi Ideologis: Secara teologis dan politik, Nabi ﷺ tidak menggunakan kata “Malik” karena istilah tersebut sering kali berkonsekuensi pada pengakuan kedaulatan permanen atau hak ketuhanan atas bumi Allah. Dengan menggunakan diksi “Shahib”, Nabi ﷺ memberikan pengakuan administratif tanpa memberikan legitimasi ideologis mutlak bagi penguasa yang belum tunduk pada syariat.
Salam yang Berprinsip: “Salamun ‘ala Manit-taba’al Huda”
Diplomasi Islam menempatkan akidah di atas formalitas politik. Kalimat “Salamun ‘ala manit-taba’al huda (Salam (keselamatan) bagi siapa yang mengikuti petunjuk),” adalah bentuk iktibas (pengambilan) dari ayat Al-Qur’an yang mengandung implikasi diplomatik yang tegas:
- Ajakan Dakwah yang Tegas: Salam ini bukan sekadar basa-basi lintas agama, melainkan seruan langsung bagi penerimanya untuk mengevaluasi landasan keimanannya.
- Identitas yang Jelas: Islam tidak mengenal “salam gado-gado” yang mengaburkan batas kebenaran demi kepentingan pragmatis.
- Keselamatan Bersyarat: Pesan ini menegaskan bahwa perdamaian dan keselamatan hakiki secara politik maupun spiritual hanya dapat dicapai dengan mengikuti jalan hidayah (Islam).
Visi Politik Luar Negeri: Dakwah, Jihad, dan Peringatan “Al-Fallahin”
Surat ini merefleksikan fondasi Siyasah Kharijiyah (Politik Luar Negeri) Islam yang berorientasi pada Hamli Dakwah (mengemban dakwah). Tujuan utama negara Islam adalah menjadi Ri’asatun Amatun (Kepemimpinan Umum) yang menjalankan syariat dan memastikan risalah Islam sampai ke seluruh dunia tanpa penghalang.
Nabi ﷺ menawarkan pilihan binari yang sangat jelas:
- Masuk Islam: Mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban secara total.
- Membayar Jizyah: Tunduk di bawah naungan otoritas Islam sebagai tanda pengakuan politik.
Poin krusial yang sering terlupakan adalah peringatan Nabi ﷺ tentang “Al-Fallahin” (kaum petani/rakyat jelata). Nabi ﷺ memperingatkan Heraklius bahwa jika ia menolak, maka ia akan menanggung dosa rakyatnya (ismul fallahin). Dalam kajian komunikasi politik, penggunaan istilah “Al-Fallahin” adalah sebuah kinayah (metonimi) bagi massa non-Arab (Ajam). Ini adalah gertakan diplomatik yang cerdas: Nabi ﷺ memposisikan penguasa sebagai “penghalang fisik” antara rakyat dan kebenaran. Jika penguasa tetap menjadi penghalang, maka jihad menjadi instrumen sah untuk meruntuhkan tembok tersebut agar dakwah bisa sampai ke tengah rakyat.
Konsep Keadilan “Falaka wa Alaika”
Puncak dari tawaran politik Islam adalah keadilan hukum yang mutlak. Hal ini tercermin dalam kalimat: “Falakil muslimin wa alaika ma alaihim (Bagimu hak seperti kaum Muslim dan atasmu kewajiban seperti mereka).”
Melalui teknik retorika Attibaq wal Muqabalah (pertentangan kata Laka [hak] dan Alaika [kewajiban]), Nabi ﷺ menawarkan kontrak sosial yang revolusioner. Jika seorang kaisar masuk Islam, ia tidak lagi memiliki hak istimewa di atas hukum. Ia harus tunduk pada syariat yang sama dengan rakyat jelata. Inilah konsep keadilan yang tidak akan ditemukan dalam sistem kekaisaran manapun di dunia saat itu.
***
Warisan “Izzah” yang Terlupakan
Ketegasan dan kewibawaan (Izzah) yang tertuang dalam surat-surat tersebut bukan sekadar kata-kata, melainkan kekuatan psikologis yang nyata. Sejarah membuktikan bahwa tinta diplomasi ini telah meruntuhkan mental lawan sebelum pedang terhunus. Hal ini memuncak pada peristiwa Perang Tabuk, di mana 200.000 pasukan Romawi memilih untuk mundur dan menghindari konfrontasi saat mendengar pasukan Muslimin yang hanya berjumlah 30.000 orang bergerak maju. Haibah (rasa gentar) yang dirasakan Romawi adalah hasil dari konsistensi diplomasi Nabi ﷺ yang memosisikan Islam sebagai Sulthan Nashir—kekuasaan yang menolong dakwah.
Dunia hari ini mungkin memiliki teknologi komunikasi yang canggih, namun kita sering kehilangan esensi dari diplomasi itu sendiri: Izzah. Sebuah bangsa yang kehilangan identitas dan prinsip di hadapan kekuatan dunia tidak akan pernah memiliki wibawa.[]
Disarikan dari kajian dengan tema tersebut di NSTV: